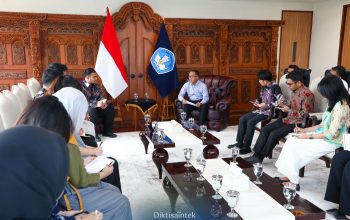Oleh: Guruh Ramdani*
INDONESIAUPDATE.ID – Sejauh pengamatan saya, anak-anak yang langganan juara melukis di masa kanak-kanak, apalagi juara lomba mewarnai, sangat jarang yang jadi seniman hebat ketika mereka sudah besar. Karena imajinasinya tidak berkembang sesuai hakikatnya, dan dipola secara sejak dini oleh pendidikan sanggar. Sehingga sepintas lalu memang gambarnya bagus. Tapi tidak ada beda antara anak sanggar satu dengan yang lainnya, atau kesan keseluruhannya, “seragam.” Gaya menggambarnya pasti dekoratif, alat lukisnya sama (pastel), gradasi dan warnanya serupa, dan gambarnya sudah bisa dipastikan selalu riuh dan padat, nyaris sangat minim ruang kosong untuk bernafas.
Dulu saya kenal dengan seorang pelukis cilik yang langganan juara, bahkan sampai mendapatkan prestasi internasional, dan pada waktu itu (tahun 1980-an) sudah hebat sekali bisa diliput TVRI. Tapi tragisnya, test masuk ke perguruan tinggi seni rupa saja dia tidak lolos. Hari ini eksistensinya di bidang seni rupa tidak pernah terdengar sama sekali.
Anak-anak yang sering menang lomba karena dipola dengan didikan semacam itu, secara mental menganggap keputusan lomba (yang dilembagakan oleh panitia) sebagai sarana untuk meneguhkan keyakinannya, bahwa “gambar saya hebat, dan gambar yang demikianlah yang benar.” Celakanya, jika hal ini sudah menjadi ideologi mereka, akan membuat sang anak yang belum kuat daya saringnya akan mandeg kemampuannya pada titik tersebut. Karena wawasannya masih terbatas, terutama dalam soal seni rupa yang merupakan samudra yang luas tersendiri mempersoalkan estetika dan imajinasi, daripada soal benar-salah. Sehingga pada level berikutnya saat mendapatkan pelajaran yang lebih tinggi dengan guru yang lain,“ secara otomatis ilmu baru itu akan ditolak oleh alam bawah sadarnya.”
Lebih jelasnya begini, dalam level anak-anak, gambar dia yang seperti itu memang bagus, namun ketika sudah dewasa, gambar seperti itu tidak akan mewakili ekspresi orang dewasa, dan akan dianggap sebagai gambar anak kecil. Orang dewasa, pasar kerja, dan dunia seni rupa akan minta seorang seniman mempunyai kemampuan banyak hal, entah itu kemampuan menggambar ilustrasi, kartun, lukisan realistik, pengetahuan akan alat dan bahan yang beragam, dan sebagainya. Bukan hanya merupakan gambar dekoratif tanpa dituntut pengaplikasian hukum perspektif serta dibuat hanya menggunakan pastel atau crayon dengan gradasi warna yang berulang seperti itu-itu saja.
Nah anak-anak yang sering juara dengan pola seperti di atas itu secara mayoritas tidak mau keluar dari zona nyamannya, dan ketika masuk ke perguruan tinggi, materi test-nya jauh berbeda dengan ketika lomba, alat yang wajib dipergunakan pada saat test-nya pun bukan crayon dan pastel.
Seperti sebuah ungkapan, “supaya ilmu mudah masuk, diperlukan kerendahan hati”. Jika mentalitas juara diiringi kerendahan hati untuk selalu belajar dan menerima serta melihat kemungkinan baru, maka sang anak akan lolos, dan di masa depan serta punya peluang untuk berprofesi di bidang seni atau menjadi seniman besar.
Tapi seberapa banyak yang demikian? Mentalitas umum yang terbentuk justru, ketika dia biasa juara lalu kalah, maka dia akan mengidentifikasikan dirinya “salah.” Situasi ini diperparah oleh ambisi orang tuanya yang selalu menuntut dia untuk jadi juara yang turut menyalahkannya juga. Karena sudah tidak asyik lagi dan jenuh dengan melukis, maka tidak mengherankan jika di masa yang seharusnya mereka tampil dengan maksimal saat dewasa justru mentalnya sudah drop dan “eneg” berkarya. Dampaknya dia akan mogok untuk berkarya lagi.
Lantas dengan demikian, apakah berarti memasukan anak ke sanggar itu jelek? Ya tidak demikian juga. Ada juga sanggar-sanggar yang memang berorientasi untuk mengeksplorasi potensi dan keunikan masing-masing anak, bukan memolanya dan mencetak mereka supaya selalu jadi juara. Cuma saya yakin sanggar yang demikian muridnya sedikit, alias tidak laku. Karena repotnya, orang tua juga punya ambisi lain ketika memasukkan anak ke sanggar, yaitu hasilnya harus juara lomba, dan prestasinya bisa dipakai untuk mendaftar sekolah melalui jalur prestasi. Rumit dan tidak sederhana memang. Situasi ini seringkali justru membuat si anak depresi dan tidak asyik lagi saat berkarya yang seharusnya merupakan ekspresi diri, karena diperlakukan sebagai objek pemenuhan ambisi orang tua, bukannya dididik selaku subjek yang unik, punya kesadaran diri, dan tumbuh dibesarkan dengan imajinasinya.
Pada hakekatnya anak berbakat itu tidak bisa diajari, karena kemampuannya sudah melekat dalam dirinya secara alamiah.Hal terbaik yang bisa dilakukan untuk mendidik anak yang berbakat itu adalah dengan memberinya stimulus (rangsangan) saja untuk mengasah potensinya tersebut. Bukan memolanya dan mencetaknya menjadi fotocopy sang guru.
Maka di perguruan tinggi seni rupa, para mahasiswa hanya ditugaskan untuk menggambar atau melukis suatu objek sesuai dengan kreatifitas, persepsi masing-masing. Tidak perlu ada yang sama. Ketika sang dosen membahas karya mahasiswa A dari sudut (style/isme/corak) tertentu, misalkan realis, maka chanel pembahasannya berada dalam perspektif realis, ketika karya mahasiswa B mempunyai kecenderungan untuk menghasilkan karya dengan corak impresionisme, maka sang dosen akan memindahkan chanel di pikirannya, dan mendiskusikannya dari sudut pandang tersebut, yang lain lagi mungkin surealisme, abstraksionisme, dan sebagainnya.
Tidak ada salah dan benar, yang ada adalah, “dari sudut pandang styleanu lukisan atau gambar tersebut belum maksimal, temanya perlu dipertajam lagi dari sisi…, sebaiknya disarankan begini, komposisinya akan lebih menarik jika,.. dan seterusnya.”Minggu depan mahasiswa yang sama dengan style yang sama namun dengan karya yang berbeda, bisa jadi akan mendapat penekanan pembahasan pada soal lainnya lagi. Tidak akan sama persis yang dibahas.
Secara umum, selama menempuh studi para mahasiswa akan meraba-raba kecenderungan umum diri sendiri, sampai akhirnya merasa nyaman di satu titik dan menemukan gaya pribadinya.Sehingga tatkala lulus, dalam satu angkatan tidak ada karya yang serupa, baik style, kecenderungan warna, maupun temanya.
Coba di-Googling lukisan karya perupa Indonesia yang sudah mendunia, “Nyoman Masriadi, Heri Dono, Eddie Hara, Ivan Sagito, Agus Kamal,” mereka berbeda antara satu dengan yang lainnya.
Jika anak-anak kita masih kecil, berikan saja sarana atau alat-alat pendukungnya, sediakan dan fasilitasi saja peralatan secukupnya, jangan diumbar juga (karena kalau diumbar biasanya berkaryanya sesuka hati tanpa arah), kalau sudah habis baru beli lagi. Berikan stimulus saja untuk merangsang dan memperkaya imajinasinya, entah film animasi, bahan bacaan yang banyak ilustrasinya, komik juga tidak apa-apa.
Sebaiknya diberikan yang bervariasi bentuknya. Amati kecenderungan serta minatnya, biasanya ada yang benar-benar dia suka akan digambar terus menerus dalam kurun waktu tertentu, dan kesukaan dia menggambar sesuatu biasanya berubah seiring waktu.
Ketika dia sudah bosan di situ dia akan belajar hal baru. Seiring bertambahnya usia peralatannya juga harus lebih variatif, jangan sejenis dan mentok di pensil warna atau crayon dan pastel, beri mereka cat air, cat poster, cat minyak, yang menuntut gerak motorik dan olah rasa yang berbeda. Sehingga rasa haus akan belajarnya terjaga. Begitu seterusnya, sampai berkembang.
Ikut lomba juga tidak masalah, tapi orang tua harus hati-hatidan jangan menarget dia untuk menang. Kalau menang syukur, kalau tidak, hitung-hitung latihan mental supaya dia belajar berbesar jiwa. Karena belajar berbesar jiwa mengakui keunggulan orang lain lebih sulit daripada belajar untuk menang, dan hal itu sangat bermanfaat ketika mereka dewasa kelak. Menjadi juara sebaiknya dipandang sebagai sebuah hadiah dan buah dari kerja keras, tapi bukan keharusan. Karena siapa tahu orang lain sesungguhnya lebih keras usahanya dari kita.
Lagi pula kenyataan hidup (yang akan dihadapi anak kelak) bukan hanya melulu soal, “saya adalah yang terbaik, dan harus selalu menjadi yang terbaik,” yang seringkali membuat mereka menjadi egois, mau menang sendiri, anti sosial, dan tidak bisa toleran terhadap kekurangan orang. Tapi juga menyangkut sikap kesalingtergantungan satu sama lain, atau berbagi peran. (*)
*Penulis adalah Dosen Sekolah Vokasi IPB University